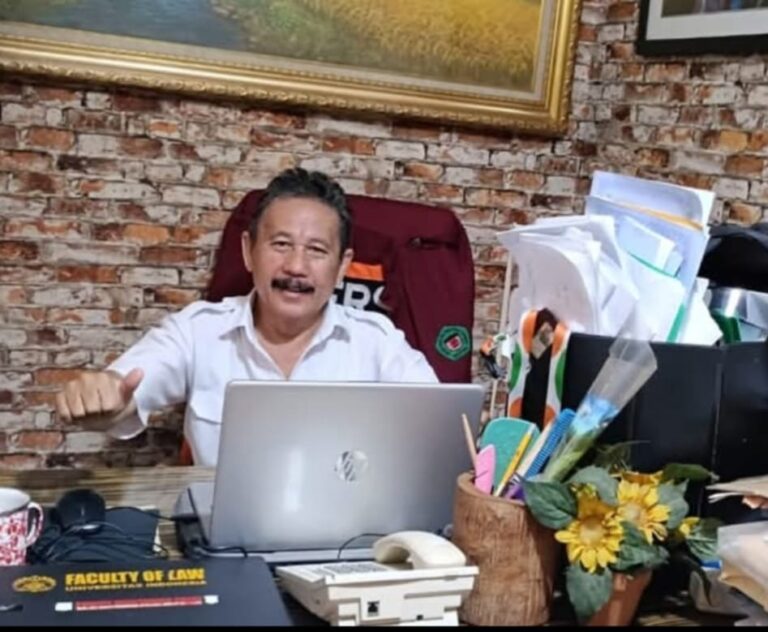Oleh: Naek Pangaribuan, Wartawan Senior, Pemerhati Hukum dan Pers
“Mulai sekarang, abang saya beri nama Kim Liong. Naga Emas,” katanya sambil tertawa.
|| SETIAP menjelang Imlek, awak selalu punya kebiasaan kecil yang sama, dengan memperlambat laju kendaraan ketika melintas di sebuah kawasan di Jakarta Selatan.
Ada patung “Kuda Api”, lampion merah bergantungan pelan-pelan ditiup angin.
Tahun ini berbeda. Di pelataran itu berdiri gagah patung “Kuda Api”, shio Tahun Baru Imlek 2577 yang dirayakan lima hari lagi tepatnya pada Selasa, 17 Februari 2026. Warnanya menyala, merah menyembur seperti bara. Awak menghentikan kendaraan, turun, lalu memotretnya.
Jepretan kamera ponsel itu seperti membuka pintu ingatan. Tak terasa, sudah 26 tahun Imlek menjadi hari libur nasional. Dua puluh enam tahun silam waktu yang tak pendek untuk sebuah perubahan sejarah.
Namun tak banyak orang tahu, bahwa di balik gemerlap lampion dan riuh barongsai, ada percakapan sederhana di sebuah ruang sempit sekitar tahun 2000 di kawasan Pluit Jakarta Utara.
Saat itu, seorang pria eksentrik yang dikenal banyak orang sebagai “Suhu Acai” memanggil awak. Orang mengenalnya sebagai paranormal. Sebagian menjulukinya “Si Raja Pelet”. Tapi di mata awak, ia lebih mirip seorang pejuang yang menyimpan keresahan.
“Bantu saya ya, Bang. Saya percaya abang pasti bisa,” katanya waktu itu.
Awak terdiam. Mengapa dia percaya kepada awak? Awak bukan tokoh besar. Hanya wartawan yang kebetulan sering meliput di DPR/MPR.
Suhu bercerita bahwa ia baru saja “turun gunung”. Katanya ia mendapat wangsit, Imlek harus dijadikan tanggal merah.
Awak tak langsung percaya pada hal-hal gaib. Tapi awak percaya pada rasa keadilan.
Pertanyaannya sederhana, mengapa hari raya budaya yang telah hidup puluhan tahun di Nusantara ini belum sepenuhnya diakui?
Awak sendiri belum terlalu paham tentang Imlek. Yang awak tahu, dulu semasa SMA, awak sering datang ke rumah teman-teman yang merayakan. Awak menerima angpao, mencicipi kue keranjang, dan ikut tertawa tanpa pernah merasa berbeda.
Belakangan awak pelajari, Imlek bukan ritual agama. Ia adalah perayaan budaya yang akarnya jauh di masa Dinasti Han, simbol sukacita panen, harapan baru, dan doa akan kemakmuran.
Tahun 2000 itu, kami mendirikan sebuah lembaga: Yayasan Lestari Kebudayaan Tionghoa Indonesia (YLKTI). Suhu Acai menjadi ketua. Awak dipercaya membantu menyusun konsep surat, merancang argumentasi, hingga melobi fraksi-fraksi di DPR.
Hari-hari itu diisi dengan diskusi panjang, perdebatan, dan langkah-langkah kecil yang kadang terasa melelahkan. Awak dan sejumlah komunitas dan anggota keluar-masuk ruang fraksi untuk beraudensi. Ada yang menerima dengan hangat. Ada yang memandang ragu.
Al hasil, sembilan dari sebelas fraksi menyatakan dukungan agar Imlek dijadikan hari libur nasional.
Presiden Gus Dur lebih dulu membuka pintu lewat Inpres Nomor 6 Tahun 2000. Namun statusnya masih fakultatif dimana yang merayakan boleh libur. Dan kemudian, Presiden Megawati Soekarnoputri menindaklanjutinya melalui Keppres yang meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional. Sejak 2002, Imlek resmi menjadi bagian dari kalender merah bangsa ini.
Hari itu, bukan hanya masyarakat Tionghoa yang bersuka cita. Itu kemenangan bagi kebinekaan. Di tengah perjuangan itu, Suhu tiba-tiba memberi awak nama baru.
“Mulai sekarang, abang saya beri nama Kim Liong. Naga Emas,” katanya sambil tertawa.
Awak tersenyum. Seorang Batak diberi nama Tionghoa. Di situlah Indonesia menemukan wajahnya yang paling indah.
Bahkan pada 2003, Museum Rekor Indonesia (MURI) memberi penghargaan sebagai pelopor perjuangan Imlek menjadi hari libur nasional. Piagam itu bukan sekadar kertas berbingkai. Ia adalah pengingat bahwa perubahan bisa lahir dari tekad dan kolaborasi lintas budaya.
Kini, ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar “Jakarta Imlekan”, ketika barongsai menari bebas di mal-mal, ketika festival kuliner Tiongha ramai dikunjungi semua kalangan, awak selalu teringat masa dibawah tahun 1998.
Masa ketika ornamen merah saja bisa dianggap ancaman. Hari ini, lampion tak lagi sembunyi. Ia menggantung tinggi di ruang publik. Itu bukan sekadar dekorasi. Itu simbol kebebasan yang diperjuangkan.
Namun ada satu mimpi yang belum awak wujudkan.
Awak ingin menulis buku berjudul: “Orang Batak Ikut Memperjuangkan Imlek Sebagai Hari Libur Nasional.”
Bukan untuk membanggakan diri. Tapi agar generasi berikut tahu, bahwa sejarah bangsa ini tidak pernah dibangun oleh satu suku, satu agama, atau satu warna saja.
Sejarah dibangun oleh mereka yang mau berdiri bersama.
Awak menatap lagi foto “Kuda Api” di layar ponsel. Api itu seperti menyala dalam dada, mengingatkan bahwa perjuangan tak pernah sia-sia.
Gong Xi Fa Cai. Semoga bangsa ini tetap jaya, makmur, dan setia menjaga keberagaman.
Bhineka Tunggal Ika, bukan sekadar semboyan, tetapi napas yang harus terus kita rawat.
[Jakarta, 12 Februari 2026/®harian posmetro.com]